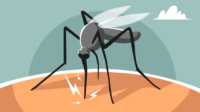60DTK – Opini : Kumpulan pengajar dan mahasiswa ilmu ekonomi di Perancis pada tahun 2000, menuliskan sebuah petisi keberatan yang memperkarakan ortodoksiilmu ekonomi di berbagai kampus sebab dipandang terbenam dalam abstraksi matematis dan terombang-ambing menjauhi sentuhannya dengan realitas.
Tuntutan pertama dari petisi tersebut ialah “kita ingin keluar dari dunia imajiner” (Suryajaya, 2013) Amsal orang yang belajar arsitektur tapi tak mampu membangun rumah, berguru aeronautika tapi tak pernah mencipta pesawat, menimba ilmu pendidikan tapi berkelakuan seperti tak terididik. Apa yang dipelajari tidak menjadi tuntunan dalam berbuat, menjawab persoalan di dunia nyata.
Realisme mensyaratkan bahwa sesuatu itu dapat disebut realis bila benar-benar mewujud dalam dunia nyata, dapat dipandang dengan mata kepala, dan tampil di ujung batang hidung kita. Melihat sesuatu dengan realis dapat diseumpamakan melihat salju, bagi orang yang belum pernah melihat salju ia akan segera yakin bahwa salju itu putih (meskipun ia sendiri belum pernah melihatnya) sebab skema konseptual orang tersebut mengharuskan salju itu berwarna putih dan bukan merah.
Keyakinan bahwa salju itu berwarna putih hanya bisa dibenarkan bila salju yang dimaksudkan benar-benar mewujud berwarna putih di dunia nyata, hal tersebut merupakan syarat sesuatu dikatakan sebagai realis(Kirkham, 2013).
Menggunakan pisau Realisme, kita akan melihat eksistensi pendidikan juga yang menjadi ruhnya, yakni ilmu. Seberapa jauh ilmu telah mengubah tatanan kehidupan manusia dalam konteks keindonesiaan hari-hari ini yang kian semraut oleh berbagai ketimpangan? Apakah skema konseptual yang dibangun oleh ilmu-ilmu yang dilembagakan dalam institusi pendidikan telah menyesaikan persoalan kongkrit di masyarakat? Atau hanya menyembunyikan kekosongannya lewat istilah mentereng yang dirumit-rumitkan tercebur dalam ritus formalistik?
Roem Topatimasang dalam bukunya Sekolah Itu Candu, secara gamblang memaparkan kontradiksi dalam dunia pendidikan. Kucuran dana pendidikan yang tidak sedikit, tidak membawa perubahan berarti dalam praktik pendidikan. Para pengajar ternggelam dalam birokratisasi pembelajaran bergaya obat nyamuk, berputar-putar pada istilah-istilah tidak menyentuh esensi yang menghidupkan istilah itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari.
Pelajar sibuk menggumuli teori tapi tidak diterangkan juntrungannya untuk apa? Apalagi relevansinya dengan realitas persoalan di masyarakatnya. Mengurung diri dalam komunitas yang rumahnya dipagari tembok-tembok tinggi.Tidak sulit menemukan kesesuaian uraian karya tersebut dalam situasi kekinian.
Menemukan kembali realisme pendidikan, kita seolah dipaksa menelusuri sungai ingatan yang kian jauh ke belakang kian bening pantulan cahayanya. Dokumen-dokumen sejarah mahakaya menjelaskan kiprah para pendiri bangsa ini, yang walaupun kekurangan gelar di belakang namanya, namun aktualnya begitu berperan menghidupkan aktualisasi pendidikan, sebagai alat membentuk perubahan dan memerdekakan kita dari belenggu penjajahan.
Tapi dari mana para pendiri bangsa itu, mendapatkan pisau analisanya dalam melihat pendidikan sebagai praktik yang tidak terpisah dari persoalan di dalam masyarakat? Yang ketika itu masih dalam era penjajahan Belanda? Bukankah sebagian mereka dipahat pikirannya oleh sekolah-sekolah milik Belanda? Tujuan Belanda saat itu untuk mempabrikasi pemuda-pemuda cerdas namun jinak, gagal mendapatkan ganjaran yang diinginkan. Ketajaman pikiran dituntun oleh niat yang luhur para pendiri bangsa membawa malapetaka bagi para komprador kapitalistik itu.
Melihat constructs pendidikan sebagai pertandingan diluar dekorasi gedung dan formalistik, kita akan pergi pada pemaparan Paulo Freire; Kekuasaan yang berlebihan telah mencirikan kebudayaan yang sejak awal telah menciptakan di satu pihak kecendrungan masokhistis untuk patuh terhadap kekuasaan dan di lain pihak kecendrungan untuk sangat berkuasa.
Kebiasaan patuh ini mendorong manusia untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dan bukan untuk berintegrasi dengan realitas. Integrasi yang merupakan tindakan khas dari rezim demokratis yang fleksibel paling tidak membutuhkan kemampuan untuk berpikir kritis(Freire, 2001).
Uraian Paulo Freire di atas memperlihatkan hubungan antara kebudayaan, kekuasaan dan pendidikan sebagai satu kesatuan utuh. Pendidikan bukanlah aktivitas yang terisolir dari realitas, dia bagian integral dari realitas itu. Sifat pendidikan yang kritis terhadap realitas mewujudkan iklim demokratisasi bagi kehidupan masyarakat yang pada ujungnya menggelorakan jiwa kebudayaan yang merdeka.
Prof. Drs. Heru Nugroho saat pidato pengukuhan guru besarnya, memberi pemarkah guna mengenali gejala patogen dunia pendidikan itu, dengan istilah “banalitas intelektual” Istilah banalitas mengingatkan kepada istilah yang ditulis Hannah Arendt, pemikir politik dari Jerman, dalam Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Istilah banalitas digunakan untuk menyebut kejahatan yang telah kehilangan ciri kejahatannya, dirasakan wajar atau biasa saja. Banalitas kejahatan terjadi karena dangkalnya refleksi manusia terhadap situasi kejahatan yang terjadi(Adinda, 2013)
Pendidikan yang didewakan sebagai pilar penyangga bangsa ini, harta satu-satunya yang berharga. tapi apa daya yang terpraktekan sungguh ironis. Pendidikan yang secara eksplisit diamanatkan agar bangsa ini kian hari kian cerdas, karena itu konstitusi mengatakan Turut Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Sebaliknya berbalik menjadi persoalan yang tak kunjung usai, malah membuat masalah bagi bangsa ini makin pelik. Semisal virus dalam tubuh manusia, kehadirannya bisa menjadi benteng kekebalan bagi tubuh, namun juga bisa membunuh tubuh itu sendiri bila ia terus membelah diri. Kanker yang tak disadari.
Sebab-sebabnya dapat diidentifikasi karena pendidikan telah kehilangan realismenya.Melenceng jauh dari cita-cita idealnya sebagai rakit yang kita pakai menuju muara pembebasan dan pemberdayaan. Kecendrungan memelihara elistisme. komersialisasi yang eksesnya sebagaian masyarakat kesulitan menjaukaunya.Kerangkeng birokratitasi yang membenamkan pendidikan sebatas urusan administrasi dan bukan sarana membiakan kristisisme. Keadaan seperti ini tak mungkin mewujudkan sesuatu yang emansipatoris. Menjadi tanah yang subur bagi status quo dan kesenjangan sosial.
Aktivitas pendidikan patut dihargai sebagai sebuah kerja sosial yang sulit penuh tantangan dan menyenangkan, bukan dan bukan meditasi mengurung diri dalam tembok-tembok serta bertujuan memelihara ortodoksi predeterministik.
Daftar Bacaan :
Adinda, A. J. (2013). Banalitas Intelektual Dalam Dunia Pendidikan Tinggi Suatu Kajian Filsafat Ilmu. Arete, 160-172.
Freire, P. (2001). Pendidikan Yang Membebaskan. Yogyakarta: Melibas.
Kirkham, R. L. (2013). Teori-Teori Kebenaran. Bandung: Nusamedia.
Suryajaya, M. (2013). Asal Usul Kekayaan . Yogyakarta: Resist Book.
Topatimasang, R. (2010). Sekolah Itu Candu . Yogyakarta: INSISTpress.
Editor : Zulkifli M.
Penulis : Pramono Pido